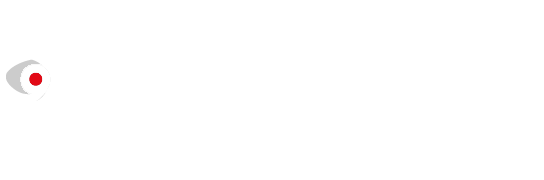BETAPAPUN Barat melepaskan atribut agama dari paradigmanya tentang alam dan manusia, yang memang dipengaruhi oleh rasionalisme naturalistik dan dualisme cartesian. Namun kita tidak selayaknya memandang sebelah mata, ketika paradigma itu memberikan keberhasilan yang gemilang bagi mereka.
Oleh: Ahmad Agus Fitriawan
Guru MTs. Yamanka Kec. Rancabungur Kab. Bogor
Hal ini disebabkan, karena paradigma Barat lebih melihat pada lapangan emÂpiris dari pada inÂtuisi. Betapapun intuisi itu benar, mereka tetap meragukannya seÂbelum dibuktikan secara empiris. Bagi mereka lapangan empiris adalah lapangan logis dan ilmiyah dalam merealisasikan suatu teori dan konsep ilmu pengetahuan.
Mungkin faktor inilah yang dapat memberikan kontribusi bagi pemikir-pemikir muslim dalam upaya mengembangkan sinyalemen-sinyalemen wahyu yang banyak membicarakan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, misÂalnya, ketika manusia dikatakan sebagai khatifah fi al-Ardh, maka bagaimana lapangan empiris membuktikannya ketika manusia berada dalam kegamangan antaÂra idealitas dan realitas. Dan juga ketika manusia dikatakan sebagai makhluk yang lebih hina dari pada binatang, lalu bagaimana lapangan empiris membuktikanÂnya ketika manusia berada antara dua sisi kebaikan dan kejahatan, kemuliaan dan kehinaan.
Pada dasamya wahyu hanyÂalah sebagai motivator di sampÂing petunjuk bagi manusia untuk merealisasikan apa yang menjadi kebaikan bagi manusia itu sendiÂri. Ketika manusia dikatakan seÂbagai khalifah sudah selayaknya manusia itu menuju kepada poÂsisi kekhalifahannya. Dan ketika manusia dikatakan sebagai makhÂluk yang lebih mulia, maka sudah semestinya manusia itu mempoÂsisikan dirinya sebagai makhluk yang mulia dan tetap menjaga kamuliaannya itu agar tidak terÂjatuh pada kehinaan.
Dalam hal ini filsafat Iqbal meletakkan semua kepercayaan pada manusia yang dilihatnya memegang kemungkinan tak terÂbatas. Kemampuan mengubah dunia dan dirinya sendiri. DenÂgan ini Iqbal membuka gambaran masa depan yang menakjubkan, ia memerdekakan manusia dengan mengajarinya bagaimana menjadi tuan nasibnya sendiri.
Menurutnya kemanusiaan adalah tujuan menuju terciptanÂya suatu rasa ideal individu, akan tetapi datangnya manusia unggul tidak akan mungkin hingga ego melampaui proses yang menÂcakup tiga tahap yang bisa dibeÂdakan: (a) ketaatan kepada huÂkum, (b) penguasaan diri sendiri yang merupakan bentuk tertinggi kesadaran diri tentang pribadi dan (c) kekhalifahan Ilahi. (Luce, 1996: 37)
Manusia unggul adalah khaliÂfah Tuhan sempurna, puncak kehidupan mental maupun fisik. Dalam dirinya ketidaklarasan kehidupan mental kita menjadi keharmonisan. Kemampuan terÂtinggi bersatu dalam dirinya menÂjadi pengetahuan tertinggi. Dalam dirinya pikiran dan perbuatan, naluri dan nalar menjadi satu.
Oleh karena itu, Islam buÂkanlah masalah yang terpecah-pecah, ia bukanlah cuma pikiran, perasaan, atau perbuatan, tetapi ia adalah “pengungkapan keseluÂruhan manusiaâ€. Ia juga bukan satu agama dalam arti kata biÂasa, namun ia adalah satu filsafat hidup yang berusaha menjaga perkembangan pribadi yang harÂmonis dan tranformasi kemanuÂsiaan.
Dengan demikian, manusia unggul adalah makhluk yang berÂpikir, dan dengan bakat transenÂdentalnya ia tumbuh dalam kesÂadaran akan dunia dan dirinya, serta keadaran akan kondisi maÂnusiawinya dalan dunia, dalam masyarakat, dan dalam waktu. Berdasarkan inilah Islam memÂbangun pola pendidikan, yang tidak terlepas dari pandangan filosofisnya, yang mencakup tiga hal, di antaranya adalah: PerÂtama, Ontologi; yang membahas asal-usul kejadian alam nyata dan di balik alam nyata. Kedua, EpistiÂmologi; yang membahas tentang kemungkinan manusia mengetaÂhui gejala alam. Dan ketiga, AkÂsiologi; yang membahas tentang sistem nilai-nilai dan teori nilai atau yang disebut etika.
Dari ketiga pandangan fiÂlosofis ini, Islam menerapkan beberapa prinsip yang menjadi pola dasar pendidikannya, di antaranya adalah: Pertama, IsÂlam memandang bahwa segala fenomena alam ini adalah hasil ciptaan Allah dan tunduk pada hukum-hukum mekanisme-Nya sebagai sunnatullah. Oleh karena itu manusia harus dididik agar mampu menghayati dan mengaÂmalkan nilai-nilai dalam hukum Allah itu.
Kedua, Islam memandang manusia sebagai makhluk yang paling mulia, karena memiliki harkat dan martabat yatrg terÂbentuk dari kemampuan-kemamÂpuan kejiwaannya, di mana akal budi-nya menjadi tenaga pengÂgerak yang membedakan dari makhluk lainnya.
Ketiga, Islam memandang manusia bukan saja makhluk pribadi, melainkan juga makhluk sosial, yang berarti makhluk yang harus hidup sebagai anggota masyarakat sesamanya. Watak sosial yang dibentuk oleh Allah dalam pribadi manusia yang seÂcara psikologis sosial disebut hoÂmososius yang memiliki instink dregarius (suka berkumpul) dan dalam bahasa Islamnya disebut ummatan wahidatan (umat yang satu).
Keempat, Islam memandang bahwa manusia adalah pribadi-pribadi yang mampu melakÂsanakan nilai-nilai moral agama dalam hidupnya, dalam arti nilai-nilai yalg menjadi doktrin Islam yang dijadikan dasar bagi proses pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat. (Langgulung, 1992 :78)
Oleh karena itu, amat sangat sejalan sekali dengan pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh dua filosof Muslim terkenal yaitu Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun yang sangat terkonsentrasi perÂhatiannya terhadap bagaimana anak didik itu seharusnya diperÂlakukan, oleh karena mengingat anak didik sebagai manusia yang mulia, makhluk yang berfikir, dapat dipengaruhi oleh herediÂtas dan lingkungan, memilliki motivasi dan kebutuhan, meÂmiliki perbedaan individu, dan selalu berubah. Keduanya mengÂgambarkan tentang bagaimana perlakuan anak didik yang sehaÂrusnya dilakukan oleh setiap penÂdidik.
Dalam hal ini mereka sepakat bahwa: Anak didik harus diberiÂkan pengetahuan agama sedini mungkin dan dilatihnya dengan baik, diberikannya suri tauladan baik di rumah, di sekolah, mauÂpun di dalam masyarakat, dibenÂtuk karakteristiknya dan selanÂjutnya dihindari dari pengaruh buruk. Begitu pula seorang penÂdidik harus sensitif terhadap keÂcendrungan, tabiat, dan gharizah anak didiknya, kemudian didekaÂti dengan bahasa mereka dan supaya pendidik memerankan dirinya sebagai orang tua mereka yang menjadi tempat curahan kaÂsih sayang. (Nasution, 1988: 65)
Dengan dernikian, pola penÂdidikan humanisme Islam dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam bentuknya yang dinamis dan inovatif. Pendidikan Islam mendasarkan diri pada teosenÂtris, yaitu berinspirasikan pada wahyu Alqur’an dan Sunnah dalam melaksanakan proses belaÂjar mengajar sebagai upaya memÂbina dan membentuk anak didik yang dicita-citakan oleh Alqur’an dan Sunnah.
Pendidikan Islam bertujuan membangun kehidupan duniÂawi, sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT. Maka proses belajar mengajar diarahkan pada pembentukan dan pengembanÂgan daya kognitif, afektif dan psikomotorik anak didik.
Pendidikan lslam memperiorÂitaskan pada nilai-nilai kebenaran mutlak yang disimbolkan melalui imtak dari pada kebenaran relatif yang disimbolkan melalu iptek, agar dengan itu anak didik mamÂpu menumbuh-kembangkan poÂtensi ilahiyahnya yang berdasarÂkan pada imtak dan iptek dan menekan gerak potensi bahimiÂyahnya yang berdasarkan pada iptek.
Inilah upaya merealisasiÂkan keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, agar tidak terdistorsi dan terdeÂviasi dari fitrahnya sebagai maÂnusia, makhluk yang lebih tinggi dan mulia dari makhluk lainnya, Islam menampilkan sebuah paraÂdigma pendidikan melalui persÂpektif humanismenya yang jusÂtru mengangkat dan memuliakan kedudukan manusia sejalan denÂgan fitrahnya sebagai Khalifah fi al-Ardh dan pengemban amanat Ilahi.
Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidik, (Jakarta: Pustaka Al- Husna, 1992), cet. ke-1.
Miss Luce-Claude Maitre, InÂtroduction to the Thought of Iqbal, alih bahasa Djohan Effendi, (JaÂkarta: Mizan, 1996), cet. ke-4.
Muh. Yasir Nasution, ManuÂsia manurut Al-Ghazali, (Jakarta: Raja Wali Press, 1988), cet. ke-1.