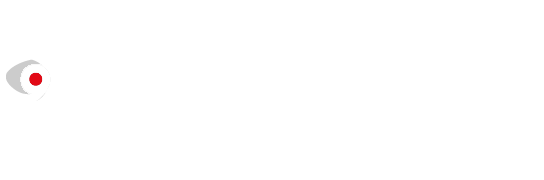KITA hargai keteguhan pemerintah untuk tidak menambah kuota impor (daging dan sapi). Ini merupakan bagian dari upaya mencapai target swasembada daging sapi. Namun, tanpa membenahi usaha ternak sapi, rantai pasok (supply chain), moda transportasi, dan RPH, gonjang-ganjing harga daging sapi setiap saat bakal terulang.
KITA hargai keteguhan pemerintah untuk tidak menambah kuota impor (daging dan sapi). Ini merupakan bagian dari upaya mencapai target swasembada daging sapi. Namun, tanpa membenahi usaha ternak sapi, rantai pasok (supply chain), moda transportasi, dan RPH, gonjang-ganjing harga daging sapi setiap saat bakal terulang.
Oleh: KHUDORI
Penggiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Para jagal dan pedaÂgang daging sapi segar mogok. Aksi itu meruÂpakan protes atas keÂnaikan harga daging yang dinilai merugikan jagal dan pedagang di pasar tradisional. Jika ada jagal dan pedagang yang memotong dan menjual dagÂing di pasar tradisional, ia akan didenda Rp 50 juta per hari. SeÂbelumnya, aksi mogok berjualan telah dilakukan pedagang daging sapi di Jakarta. Mogok dilakukan agar pemerintah turun tangan mengendalikan harga daging. KeÂnaikan harga yang tak terkendali membuat pedagang bakso, pedaÂgang makanan, serta pengusaha restoran dan katering terpukul. Apalagi daging sapi tidak mudah didapatkan di pasar.
Importir dan pemerintah salÂing tuding. Menurut importir, keÂnaikan harga terjadi karena dagÂing langka. Sumber masalahnya, pemerintah memangkas kuota impor daging dan sapi secara drastis. Pada 2011, kuota impor daging dan sapi masing-masing 100 ribu ton dan 560 ribu ekor. 2014, kuota impor daging dan sapi dipangkas tinggal 34 ribu ton (tinggal 34 persen dibanding tahun lalu) dan 283 ekor (50 persÂen). Menurut importir, pemerÂintah terlalu optimistis dengan kemampuan pasokan sapi doÂmestik. Pendek kata, menurut importir, Indonesia belum siap menghadapi pemotongan kuota impor sebesar itu.
Dilihat dari transmisi harga, kenaikan harga daging saat ini tidak wajar. Transmisi harga dari peternak ke konsumen bersifat asimetris. Ini menandakan pasar daging tak sehat. Dugaan ada sekelompok kecil orang yang meÂmiliki kekuatan mengendalikan pasokan, dan mengatur harga di pasar, ada benarnya. Tujuannya, agar pemerintah kembali memÂbuka impor. Modus ini juga terÂjadi pada kedelai.
Kelangkaan sapi yang dikeÂluhkan importir dan pedagang juga ada benarnya. Tetapi tentu bukan tanpa alasan pemerintah memangkas kuota impor (daging dan sapi). Pemangkasan impor didasari data populasi ternak doÂmestik. Menurut hasil survei peÂternakan, per Juni 2011 populasi sapi potong mencapai 14,82 juta ekor. Sebelumnya, data populasi ternak ini belum kita miliki. KeÂbutuhan daging nasional tahun 2012 mencapai 484.060 ton. KeÂbutuhan itu dipenuhi dari daging lokal 399.320 ton, sisanya 84.740 ton (17,5 persen) dari impor. PaÂsokan daging lokal itu setara denÂgan 2,4 juta ekor. Dengan popuÂlasi sapi potong 14,82 juta ekor, kebutuhan 2,4 juta ekor tentu memadai.
Masalahnya, data-data itu hanya angka mati di atas kertas, yang sama sekali tidak mereÂfleksikan kondisi di lapangan. Sampai saat ini struktur indusÂtri peternakan domestik untuk semua komoditas ternak, termaÂsuk sapi, sebagian besar (60-80 persen) bertahan dalam bentuk usaha rakyat dan usaha sambilan yang berciri pendidikan rendah, pendapatan rendah, manajemen dan teknologi konvensional, serta menggunakan tenaga kerja keluÂarga (Yusdja dan Winarso, 2009). Bagi peternak jenis ini, sapi adalah tabungan yang likuid yang bisa dimanfaatkan setiap saat ketika ada kebutuhan mendeÂsak. Usaha itu tersebar di banyak tempat. Tak mudah memobilisasi ternak-ternak itu untuk memasok kebutuhan mendesak.
Ternak sapi belum menjadi usaha utama karena dua hal. Pertama, akses modal melalui perbankan untuk pengembangan peternakan komersial penggeÂmukan maupun pembibitan skala kecil (10-50 ekor per periode 2-4 bulan) cukup sulit diperoleh. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga kerja, sebagai pencari pakan hiÂjauan yang membatasi jumlah pemilikan ternak. Akibatnya, peÂternak sulit meningkatkan jumÂlah ternak, sehingga sapi betina usia produktif terpaksa harus jadi ternak konsumsi. Padahal, untuk menambah populasi, pemotongan sapi betina produktif harus dihindari.
Jika pun ternak sudah terkumÂpul, tidak mudah mendistribusiÂkan dari produsen ke konsumen. Ini terjadi karena jalur distribusi dari produsen ke konsumen amat panjang. Ironisnya, dalam rantai distribusi yang panjang itu, marÂgin tidak terbagi merata. Pangsa terbesar margin pemasaran ada pada pedagang besar. Namun yang menikmati keuntungan besar justru para jagal. Artinya, margin keuntungan tidak terdisÂtribusi adil. Selain itu, kita beÂlum memiliki moda transportasi khusus. Selama ini sapi dari NTT atau NTB diangkut menggunakan kapal (umum). Ongkos angkut mahal karena, saat balik, kapal kosong. Ini salah satu yang memÂbuat harga daging sapi lokal lebih mahal ketimbang impor. Lagi pula, karena kapal tak didesain khusus, selama perjalanan sapi bisa stres dan susut bobot.
Yang tak kalah pelik adalah keberadaan rumah pemotongan hewan (RPH). Saat ini baru ada 25 RPH bersertifikat. Keberadaan RPH bersertifikat amat penting untuk menjamin kebutuhan konÂsumen dan industri berbahan baku daging sapi. Sejumlah RPH inilah yang bakal menjamin pasoÂkan kebutuhan daging konsumen yang beragam dan berbeda-beda. Masalahnya, selain RPH bersertiÂfikat jumlahnya belum banyak, kapasitasnya juga terbatas. Kita hargai keteguhan pemerintah untuk tidak menambah kuota imÂpor (daging dan sapi) tahun ini. Ini merupakan bagian dari upaya mencapai target swasembada daging. Namun, tanpa membenaÂhi usaha ternak sapi, rantai pasok (supply chain), moda transportaÂsi ,dan RPH, gonjang-ganjing harÂga daging sapi setiap saat bakal terulang. (*)